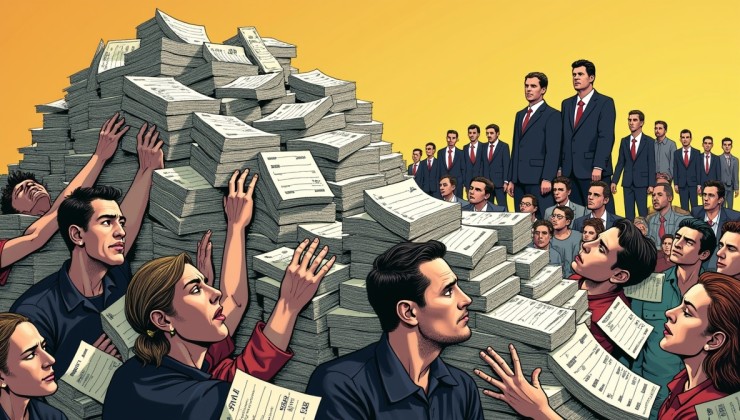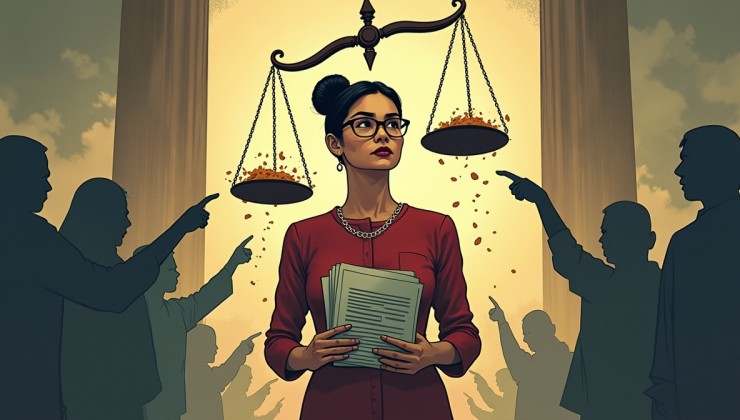
Berita Terbaru
Sri Mulyani dan Karma Wajib Pajak: Ketika Menteri Keuangan Dihantam Ketidakpastian Hukum
Oleh: Rinto Setiyawan
Ketua Umum Ikatan Wajib Pajak Indonesia
Anggota Majelis Tinggi Partai X
Wakil Direktur Sekolah Negarawan X Institute
Pada 3 September 2025, Menteri Keuangan Sri Mulyani menuliskan sebuah refleksi emosional di akun Facebook-nya, menyusul penjarahan rumah pribadinya di Bintaro, Tangerang Selatan. Ia menyebut bahwa serangan itu dilakukan oleh orang-orang “terlatih dan terkoordinasi”, dan menyatakan bahwa apa yang dirampas dari rumahnya bukan hanya barang. Melainkan juga rasa aman, harga diri, dan dalam kata-katanya, rasa kepastian hukum di Bumi Indonesia.
“Lukisan Bunga itu telah raib lenyap seperti lenyapnya rasa aman, rasa kepastian hukum, dan rasa perikemanusiaan yang adil dan beradab di Bumi Indonesia,” tulis Sri Mulyani dalam unggahan yang viral dan telah disukai lebih dari 4.000 kali.
Namun, justru pada titik inilah publik mulai bertanya: Bukankah rasa kehilangan itu selama ini telah lama dialami oleh jutaan wajib pajak di Indonesia, dan justru di bawah sistem yang dirancang dan dilindungi oleh kementerian yang dipimpin Sri Mulyani sendiri?
Otoritarianisme Fiskal dan Ironi Rasa Keadilan
Banyak kalangan, terutama dari kelompok wajib pajak, telah lama menyuarakan betapa sulitnya mencari keadilan di dunia perpajakan. Di bawah kendali Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan, sistem perpajakan Indonesia telah mengalami gejala yang semakin mendekati otoritarianisme. Kewenangan fiskal yang begitu besar tidak hanya digunakan untuk menarik pajak dari rakyat. Tetapi juga melindungi institusi-institusi di bawahnya dari kritik dan evaluasi.
Bayangkan saja: menurut data dan analisis dari tim analis Ikatan Wajib pajak Indonesia (IWPI), terdapat lebih dari 6.000 peraturan perpajakan yang harus dipahami oleh wajib pajak, baik individu maupun badan usaha. Tumpang tindih pasal, ketidakjelasan norma. Sehingga ketidaksesuaian antara undang-undang (UU) dan regulasi teknis menjadi mimpi buruk harian bagi rakyat yang ingin patuh.
Lebih jauh lagi, ketika Ikatan Wajib Pajak Indonesia (IWPI) pernah menanyakan secara resmi melalui PPID Kementerian Keuangan tentang pengakuan Indonesia sebagai negara hukum. Jawaban yang diberikan adalah lempar tanggung jawab ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Sebuah ironi besar bagi kementerian yang dipimpin oleh orang yang mengaku menjunjung tinggi konstitusi dan adab hukum.
Pengadilan Pajak: “Zona Bebas Konstitusi”?
Ketika perkara perpajakan masuk ke Pengadilan Pajak, harapan akan keadilan justru semakin kabur. Laporan dari berbagai organisasi advokasi hukum menyebutkan bahwa majelis hakim di Pengadilan Pajak seringkali tidak mengakui keberlakuan UU Administrasi Pemerintahan. Sebuah undang-undang yang justru menjadi dasar evaluasi prosedur legal dalam sistem birokrasi.
Anehnya, abstain-nya lembaga-lembaga pengawasan, seperti Inspektorat Jenderal Kemenkeu, Komisi Pengawas Perpajakan, hingga Ombudsman Republik Indonesia dalam memberikan sanksi atau catatan keras terhadap pelanggaran administrasi oleh pegawai DJP dan DJBC. Hal ini menjadi bukti kuat bahwa Sri Mulyani telah membangun tembok kekuasaan fiskal yang nyaris tak tertembus hukum.
Ketika Rasa Dilanggar Kembali pada Sang Penguasa
Sri Mulyani kini menulis bahwa hukum telah lenyap. Ia merasa harga dirinya koyak. Namun bukankah itu juga yang dirasakan oleh para wajib pajak yang hartanya disita secara sewenang-wenang? Bukankah itu yang dirasakan oleh pelaku usaha yang divonis bersalah karena sistem hukum pajak yang tak transparan? Bukankah itu yang dirasakan oleh masyarakat saat melihat DPR menikmati gaji dan tunjangan bebas pajak. Sementara mereka diperas dari pagi hingga malam oleh negara yang mengaku sedang berhemat?
Publik tentu tidak membenarkan tindakan anarki. Tapi jika seorang Menteri Keuangan merasa bisa mengajarkan adab kepada rakyat, sementara sistem fiskalnya mengabaikan keadilan, menginjak akal sehat, dan membungkam kritik maka tidak heran bila kemarahan rakyat akhirnya meledak di luar kendali sistem yang tak lagi dipercaya.
Penutup: Karma Fiskal dan Cermin Kepemimpinan
Mungkin yang menimpa Sri Mulyani adalah bentuk karma dari otoritarianisme fiskal yang selama ini ia pelihara. Mungkin ini adalah peringatan bahwa jabatan bukan tameng abadi dari murka publik. Dan mungkin ini saatnya kita bertanya ulang: bagaimana bisa seorang Menteri Keuangan bicara soal adab dan perikemanusiaan, sementara ia menutup kolom komentar di media sosial, dan membiarkan keadilan fiskal mati perlahan?
Indonesia tidak butuh pemimpin yang hanya puitis di saat krisis. Indonesia butuh pemimpin yang adil sebelum rakyat menuntutnya dengan cara yang tidak diatur dalam undang-undang.